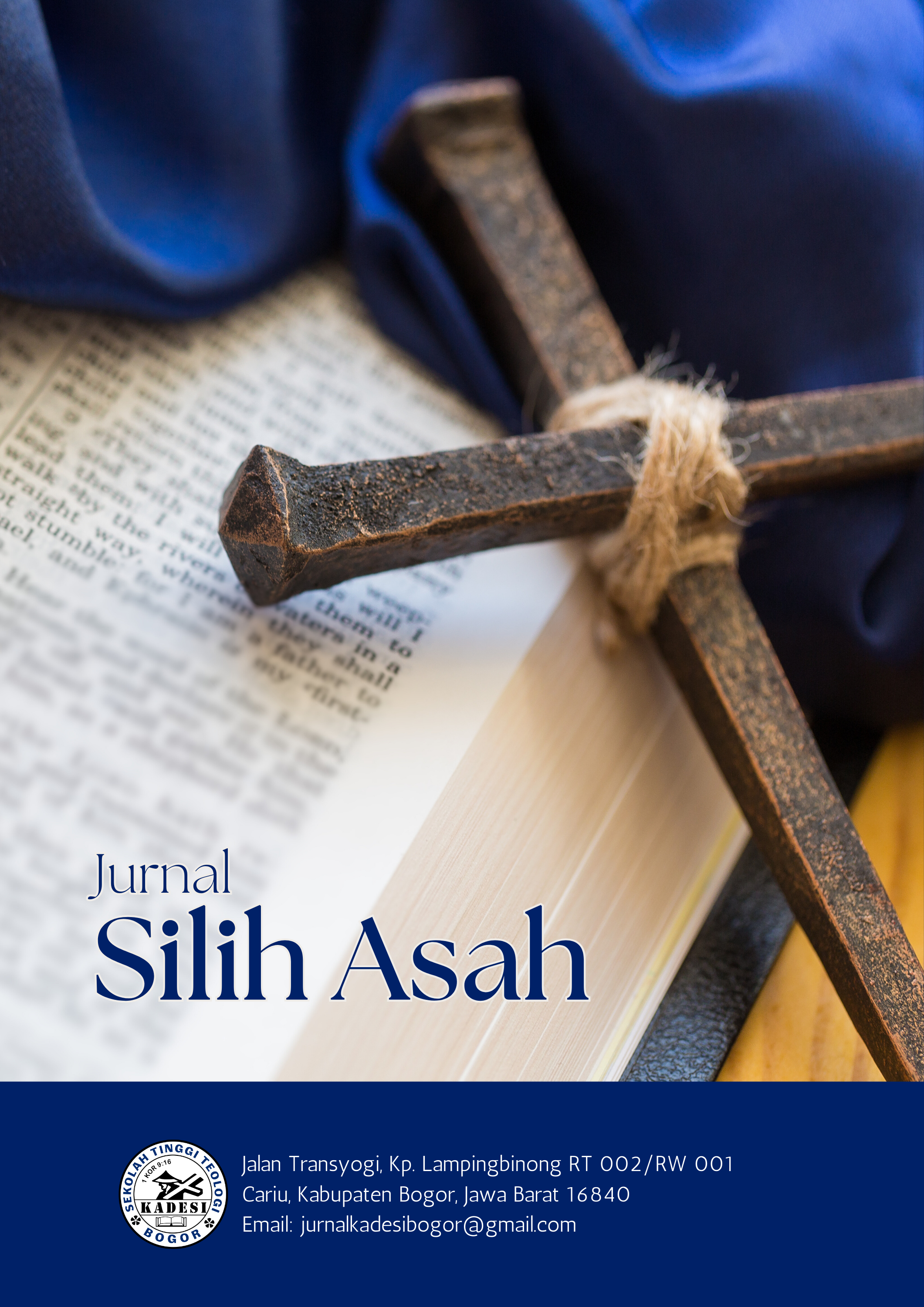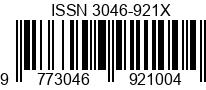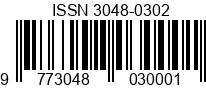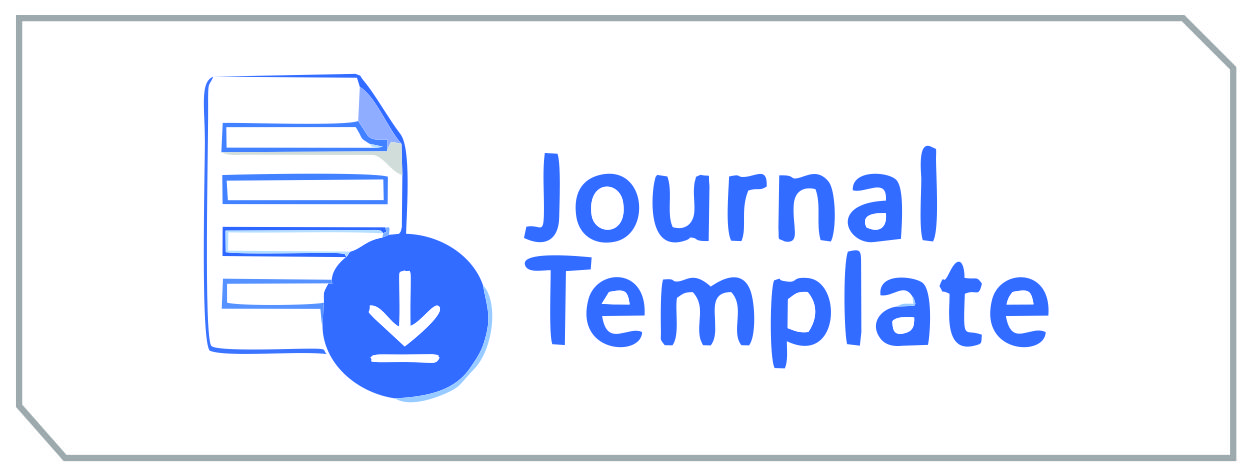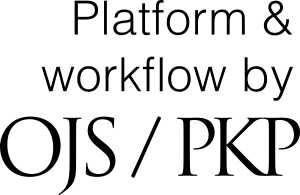Makna Teologis Prinsip Sosial Masyarakat Mamasa
“Sitayuk, Sikamase, Sirande Maya-Maya”
DOI:
https://doi.org/10.54765/silihasah.v2i2.95Keywords:
Makna Teologis, Masyarakat Mamasa, Prinsip Sosial: Sitayuk, sikamase, sirande maya-maya.Abstract
Budaya dan gereja merupakan dua hal penting yang tidak dapat terpisahkan. Terdapat tradisi, kebiasaan dan prinsip-prinsip sosial yang berlaku dalam masyarakat pada setiap kebudayaan yang bersesuaian dengan ajaran gereja menjadi dorongan oleh penulis untuk menyusun penelitian ini. Melalui karya ilmiah ini, diharapkan dapat menggali, menemukan, selanjutnya menyajikan nilai dari prinsip sosial masyarakat Mamasa yakni sitayuk, sikamase, sirande maya-maya sebagai sebuah kearifan local salah satu budaya yang memiliki makna teologis sebagaimana menurut hipotesa penulis bersesuaian dengan prinsip-prinsip persekutuan bergereja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif hasil observatif dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membawa gereja yang ada dalam masyarakat atau wilayah Mamasa untuk dapat menilai prinsip sosial ini sebagai prinsip yang Alkitabiah sehingga senantiasa dapat melestarikannya dalam menjalani kehidupan baik bermasyarakat maupun bergereja.
References
Allo, A. (2016). Sejarah Perjuangan Rakyat Mamasa melawan Gerombolan DII/TII dan Pasukan Bn.710 (1950-1965): Perjuangan Mempertahankan NKRI dan Harga Diri. Gereja Toraja Mamasa.
Bevans, S. B. (2002). Model-Model Teologi Kontekstual. Penerbit Ledalero.
Buijs, K. (2009). Kuasa Berkat dari Belantara dan Langit: Struktur dan Transformasi Agama Orang Toraja di Mamasa Sulawesi Barat. Ininnawa.
Concilium, International tijdschrift voor theologie. (n.d.). Concilium, International Tijdschrift Voor Theologie.
Hasil Wawancara Bersama Seorang Toko Adat Di Osango, Kabupaten Mamasa Bernama Tompo’. (n.d.). (n.d.).
Hasil wawancara oleh seorang toko sejarawan bernama Philipus D. Julum di desa Bambangbuda salah satu desa di wilayah kabupaten Mamasa. (n.d.).
Kobong, T., & Dkk. (2003). Agama dalam Praksis. BPK Gunung Mulia.
Koentjaraningrat. (2013). Pengantar Ilmu Antropologi. Rineka Cipta.
Mandadung, A. (2005). Keunikan Budaya Pitu Ulunna Salu. Pemerintah Kabupaten Mamasa.
Maryanah, T. (2013). Governance dalam Manajemen Konflik Pemekaran Kabupaten Mamasa. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan, 4 No. 1.
Moleong, & Lexy, J. (2006). Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revi). PT. Remaja Rosdakarya.
Nazir, M. (2003). Metode Penelitian. Ghalia Indonesia.
Niebuhr, H. R. (1951). Christ and Culture. Harper & Row.
Sairin, W. (1996). Gerak dan Langkah GPIB. BPK Gunung Mulia.
Sarwono. (2011). Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik. Sinar Grafika.
Sihombing, T. B. (1993). Adat dan Hukum dalam Perkawinan Batak Toba. Balai Pustaka.
Soenarja, A. (1977). Inkulturasi. Kanisius.
Susanta, Y. K., & Dkk. (2023). Penguatan Moderasi Beragama dalam Perspektif Pendidikan, Budaya, dan Tradisi Agama-agama di Indonesia. Kanisius.
Van der Weijden, F. (2004). Teologi Inkulturasi: Suatu Tanggapan Terhadap Tantangan. BPK Gunung Mulia.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Jurnal Silih Asah

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.